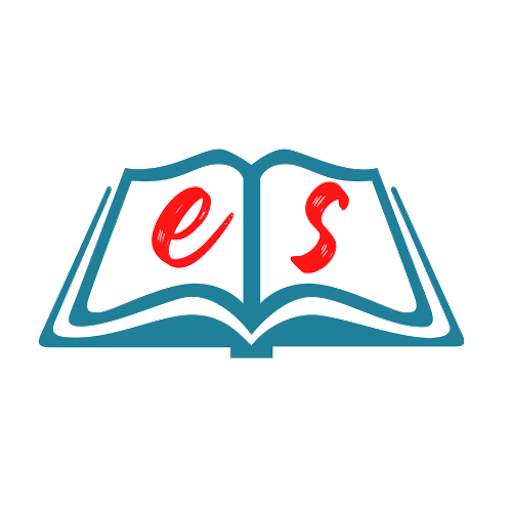Oleh: Aloys Budi Purnomo, Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata, Ketua JPIC Kevikepan Semarang
Agama-agama yang ramah lingkungan hanya dapat dikembangkan bersama semua orang, apa pun agama dan kepercayaannya. Ketika agama-agama bergerak bersama merawat Bumi, saat itulah sudah dikembangkan ekologi interreligius.
Dengan asumsi bahwa agama tak hanya bersifat teosentris melainkan juga berdimensi sosiologis dan kosmologis, Prof M Zainuddin menyampaikan opininya tentang “Agama yang Menyejukkan” (Kompas, 28/9/2021). Umat beragama saat ini dituntut mampu memahami dan menjelaskan doktrinnya dan memberikan jawaban terhadap problem kemanusiaan secara menyeluruh, termasuk problem lingkungan hidup.
Menarik bahwa disebutkan dalam perspektif Islam, pentinglah mengembangkan tiga kesatuan relasional: manusia dengan Tuhan (hablun min Allah), dengan sesama (hablun min al-nas), dan dengan semesta alam (hablun min al-‘alam). Selama ini, yang lebih dominan diwartakan adalah dua dimensi pertama. Sedangkan dimensi ketiga sering dilupakan. Menurut hemat saya, inilah justru salah satu aspek penting Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Ramah lingkungan
Sebagai pastor Katolik, pemahaman saya tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin mencakup pula komitmen Islam menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Tiga kesatuan relasi tersebut, terutama dimensi hablum min al-‘alam seperti gayung bersambut meneguhkan pemahaman saya.
Gagasan tersebut juga menjawab persoalan dan beban masa lalu ketika Abrahamic religions (Yahudi, Kristianitas, dan Islam) dituduh sebagai agama yang menjadi akar penyebab krisis ekologi. Tuduhan itu dilontarkan Lynn White di tahun 1960-an, meski di era yang sama Seyyed Hussein Nasr sangat keras menyuarakan metafisika Islam yang ramah lingkungan.
Manusia membuat Ibu Bumi berdarah bahkan hingga tidak lagi selaras dengan surga bukan karena doktrin agamanya, melainkan karena paradigma modern teknokratis yang memandang alam sekadar materi yang bisa dikeruk demi keuntungan sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Paradigma itu merupakan efek dari relativisme praktis dalam wajah antroposentrisme yang menyimpang, bahkan sesat. Ketika manusia menempatkan dirinya di pusat (antroposentris), ia akhirnya memberikan prioritas tertinggi kepada kepentingan sesaat. Akibatnya, semua yang lain menjadi relatif.
Fakta ini mendorong semua orang, apa pun agama dan kepercayaannya, mengembangkan sikap yang lebih ramah lingkungan. Alih-alih dikuasai hasrat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya dengan merusak lingkungan, tantangan terbesarnya adalah mengubah paradigma antroposentris menjadi lebih ekosentris manusiawi. Paradigmanya bukan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya secara eksploitatif terhadap alam, melainkan memikirkan masa depan nasib generasi mendatang agar tidak mendapatkan warisan alam yang hancur.
Agama-agama yang ramah lingkungan hanya dapat dikembangkan bersama semua orang, apa pun agama dan kepercayaannya. Itulah sebabnya, agama tidak dipahami sebagai realitas tunggal, melainkan plural, agama-agama. Alasannya, semua agama dan kepercayaan selalu memiliki sumber terbaik dari tradisi imannya (ortodoksi) untuk diimplementasikan dalam perawatan Bumi sebagai rumah bersama (ortopraksis).
Ketika agama-agama, termasuk kepercayaan yang biasanya dihidupi penghayat agama-agama asli (indigenous religions) atau sering disebut agama adat, saling bergandengan bergerak bersama merawat Bumi, pada saat itulah sudah dikembangkan ekologi interreligius.
Pada saat masing-masing menjadikan sumber tradisi teologis terbaiknya sebagai landasan bersikap ramah lingkungan, itulah yang disebut ekoteologi interreligius (Wilfred, 2009). Ekoteologi interreligius bahkan menjadi media untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan lingkungan yang terjadi.
Agama-agama yang ramah lingkungan dalam gerak bersama merawat Bumi merupakan tuntutan dalam menghadapi Bumi yang ditimpa krisis ekologi dalam dua abad terakhir. Perwujudan iman (ortopraksis) dalam perawatan Bumi melalui sikap ramah lingkungan bukanlah opsional, melainkan sebuah imperatif yang mendesak dijalankan. Agama tidak lari dari tanggung jawabnya, melainkan wajib terlibat merawat lingkungan.
Dalam praksis itu, agama-agama bahkan bisa meninggalkan masa lalu yang “berseteru” untuk “bersekutu” menghadapi persoalan yang sama. Dengan cara itulah, Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam dimensi hablum min al-‘alam bersinergi dengan Kristianitas yang menghadirkan kabar gembira bagi segala makhlum dalam dimensi shalom-nya.
Bahkan, daya salam Buddhis namo buddhaya semoga sekalian makhluk berbahagia, sapaan oom shanti oom dalam perspektif Hindu, serta salam kebajikan dari agama Konghucu kian memperteguh sinergi agama-agama yang ramah lingkungan. Dengan demikian semua dan siapa saja akan selalu rahayu tata tentrem kerta raharjo berpadu dengan salah satu spirit kepercayaan di negeri ini dari sekian banyak lainnya.
►https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/08/agama-agama-yang-ramah-lingkungan/